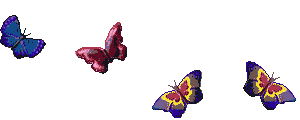Sabtu, 14 Februari 2009
Orang banyak yang tidak percaya ketika mendengar perjalanan hidup saya. Banyak yang bilang saya berbohong dan hanya mengarang-ngarang apa yang saya ceritakan. Memang jarang seorang anak janda tukang cuci kini bisa duduk di kursi CEO beberapa perusahaan nomor satu di Indonesia, seorang pengusaha muda ternama. Tapi perjalanan hidup saya adalah kenyataan, bukti bahwa Allah-lah Perencana paling sempurna. Cukuplah kita menjalankan perintahNya, dan Dia yang akan menjaga serta membimbing langkah kita.
Dan kisah hidup saya, dimulai dari sehelai sajadah lusuh.
***
Saat itu bulan Februari tahun 1979
Matahari dengan semangat memancarkan cahayanya dari balik kaca-kaca jendela gedung tempat saya bekerja. Gagang sapu di samping saya menjadi teman menahan lapar. Sesekali saya genggam, saya mainkan, saya putar-putar, berusaha melakukan apapun untuk melupakan perut saya yang keroncongan. Sebenarnya saya punya jatah makan siang, tapi uang itu harus saya simpan untuk makan malam Ibu dan kedua adik saya.
Saat itu usia saya baru masuk 18 tahun. Remaja lulusan SMA yang terpaksa bekerja karena tidak punya biaya kuliah. Ibu saya janda. Seorang tukang cuci yang upahnya hanya cukup untuk makan, uang sekolah adik-adik saya, dan sedikit pengeluaran lain. Kami tidak sanggup menanggung keegoisan saya yang sangat ingin merasakan bangku kuliah. Akhirnya saya terpaksa bekerja, membersihkan sebuah gedung yang disewa oleh perusahaan asuransi di bilangan Jakarta Utara, dekat Istana.
Kalau memikirkan masa muda saya, sering tidak habis pikir. Betapa semangat jiwa muda saya menjadi pendorong utama untuk tetap bertahan, membantu Ibu sebisa mungkin. Setiap hari saya harus menempuh jarak dua jam untuk pulang ke rumah. Sebenarnya kalau sepenuhnya ditempuh dengan bus kota, hanya akan memakan waktu setengah jam, tapi uang saya tidak cukup untuk membayar tarif bus saat itu. Jadi saya harus mencari akal untuk menghemat biaya transportasi namun tidak terlalu menguras tenaga saya.
Rumah kontrakan kami waktu itu terletak dibilangan Blok M (Saat ini sudah hancur untuk pembangunan gedung). Mugi, teman saya yang bekerja sebagai satpam tinggal di daerah Tanah Abang. Ia pun bersedia membantu saya mengatasi urusan transportasi. Setiap pagi saya naik bus dari Blok M ke Tanah Abang. Sekali naik waktu itu masih Rp. 25. Saya turun di depan Gedung PBB, dimana Mugi sudah menunggu saya dengan sepedah kumbangnya. Dari situ saya membonceng Mugi sampai ke tempat kerja kami. Pulangnya saya menumpang motor Pak Sim, pegawai perusahaan asuransi, sampai ujung Senayan, dari situ saya jalan kaki sampai rumah.
Hidup kami saat itu terlalu miskin. Untuk membantu keadaan, saya biasa melakukan puasa Senin Kamis. Kalau sedang puasa, saya biasa mampir di warung nasi dan membeli satu telur rebus untuk berbuka, seharga Rp. 5. Biasanya saya menikmati telur rebus itu di atas jembatan penyebrangan sambil memperhatikan mobil-mobil yang berlalu lalang. Sering saya mbatin, kenapa nasib kami kok sampai begini. Apa mungkin saya bisa menggantikan posisi bapak, menghidupi ibu dan adik-adik perempuan saya. Astaghfirullah! Tapi saya langsung mohon ampun pada Gusti Allah. Seperti tidak percaya saja bahwa jodoh, rezeki, mati sudah ada yang mengatur. Lalu saya akan mulai berjalan lagi, menikmati udara malam, kadang sambil bersenandung lirih menghibur hati.
***
Suatu hari terjadi kegemparan di tempat saya bekerja. Kakak dari pimpinan kami datang berkunjung. Saya sempat melihatnya beberapa kali sebelum itu. Pria separuh baya dengan badan tegap tinggi besar. Kumisnya lebat, semakin mempertegas wibawanya. Namanya Pak Risman, yang kini saya dan anak-anak saya panggil Ayah. Beliau orang yang cukup penting saat itu. Direktur utama Bank Indonesia.
Setelah sekitar 20 menit Pak Risman datang, tiba-tiba Mugi masuk ke kamar mandi, dan langsung menepuk punggung saya. Saat itu saya sedang membersihkan WC kamar mandi tempat saya bekerja.
“Gawat Ga! Gawat!” Mendadak saya melepas gagang pembersih WC yang sedang saya genggam.
“Gawat apa sih Gi?”
“Pak Risman marah-marah tuh di ruangan boss.”
“Hah? Kenapa emang?”
“Gara-gara satu kantor gak ada yang punya sajadah! Tadi dia mau sholat dzuhur, niatnya mau pinjem sajadah, tapi ternyata gak ada yang bawa. Sampe adeknya sendiri aja, boss kita itu, Pak Hidayat, gak punya sajadah juga. Dia langsung marah sama Pak Hidayat, bilang, ‘Apa satu kantor gak ada yang inget urusan akherat? Gimana mau berkah usaha kamu Hidayat? Musholah saja gak ada. Jangankan Musholah, satu pun gak ada yang punya sajadah? Kelewatan!’” Mugi berusaha meniru kata-kata Pak Risman.
“Saya punya kok sajadah.”
“Kamu punya? Kenapa baru bilang. Cepat pinjamkan ke Pak Risman. Sebelum dia semakin marah pada Pak Hidayat. Bisa gawat nanti kita-kita juga yang kena kalau Pak Hidayat kesal.”
Dengan gugup saya segera berlari ke gudang belakang, tempat saya biasanya sholat. Segera melipat sajadah lusuh saya dan membawanya ke ruangan Pak Hidayat. Di depan pintu ruangan yang tertutup, Ibu Yanti sekertaris Pak Hidayat sedang mundar-mandir kebingungan. Suara Pak Risman yang sedang menasihati adiknya terdengar sampai ke luar ruangan. Saya segera menyodorkan sajadah merah milik saya kepada Ibu Yanti. Mata beliau langsung bersinar, lega akhirnya ada yang membawa sajadah di kantor itu. Ibu Yanti langsung mengambil sajadah saya dan mengibaskan tangannya tanda saya boleh pergi kembali ke belakang.
Namun setengah jam kemudian Ibu Yanti datang ke ruang belakang tempat para pesuruh, tanpa membawa sajadah saya. Mukanya sangat serius. Seketika jantung saya mulai berdetak. Sepertinya ada yang tidak beres.
“Arga!”
“Sa...saya Bu?”
“Iya kamu Arga. Kamu dipanggil Pak Hidayat sekarang juga. Cepat Arga jangan malah bengong disitu. Sekarang!”
Lutut saya lemas. Jemari saya bergetar. Jantung saya serasa hampir pecah saking berdetak dengan kencangnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Pikiran saya langsung melayang entah kemana. Bagaimana kalau saya dipecat? Sedang adik-adik saya masih harus sekolah. Namun saya sudah tidak ada pilihan lain karena Ibu Yanti sudah menarik tangan saya, menyeret saya ke ruangan Pak Hidayat.
Di dalam Pak Hidayat duduk di kursinya dengan muka masam. Tapi Pak Risman yang duduk di kursi tamu terlihat lebih gahar lagi. Saya bisa merasakan badan saya sedikit mengigil. Keringat dingin mulai mengalir di dahi saya. Saya melangkah perlahan mendekati meja Pak Hidayat.
“Duduk kamu.” Pak hidayat mempersilahkan. Pak Risman berdiri mendekati saya.
“Siapa nama kamu nak?” Tangannya menyentuh bahu kanan saya. Saya terperangah, tidak menyangka dari perawakan sangar itu keluar suara yang sangat lembut menenangkan.
“Ar...Arga Pak.” Jawabku gugup.
“Berapa umur kamu Arga?”
“18 Tahun Pak.”
“Benar kamu pemilik sajadah merah ini?” Pak Risman memegang sehelai sajadah lusuh berwarna merah milik saya.
“I... ii..iya benar pak, itu sajadah saya.” Beliau lalu menarik kursi ke hadapan saya, duduk, dan memegang tangan saya yang sudah dingin karena ketakutan.
“Nak Arga, berapa gaji kamu sebulan?”
“9,500 Pak.” Saya memberanikan diri untuk menatap Pak Hidayat, takut jawaban saya membuatnya marah.
“Lalu untuk apa uang itu?” Pak Risman bertanya lagi.
“Untuk biaya sekolah adik-adik saya Pak.”
“Orang tua kamu?”
“Ayah saya sudah meninggal, jatuh dari gedung waktu jadi kuli bangunan. Ibu sekarang tukang cuci Pak.”
“Kenapa kamu tidak melanjutkan sekolah, Nak?”
“Tidak ada biaya Pak.”
“Kamu mau kuliah?” Mendadak saya mengangkat kepala saya. Tidak percaya akan apa yang baru saya dengar. Kuliah? Benarkah saya mendengar kata ‘kuliah’? kata yang berusaha saya hapus dari kepala saya. Keinginan yang mustahil. Mimpi yang akan selalu jadi fatamorgana. Dan kini seorang laki-laki tak dikenal menawarkan saya untuk kuliah? Ya Allah, sungguhkah?
“Kenapa diam? Kamu tidak ingin melanjutkan kuliah?”
“Mau Pak, tapi bagaimana caranya?”
“Arga, kalau kamu benar-benar ingin kuliah, Bapak akan dengan senang hati menanggung biaya kuliah kamu.” Untuk beberapa saat saya menatap mata lelai itu. Perlahan wajahnya mulai kabur karena mata saya tidak sanggup lagi menahan butir-butir air mata. Tangan saya semakin bergetar. Kali ini tidak hanya jemari saya yang dingin tapi juga kedua kaki saya. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibir saya. Rasanya sekujur tubuh saya lemas. Benarkah?
“Ke..kenapa saya Pak?” Akhirnya sepenggal kalimat itu bisa keluar. Pak Risman tersenyum.
“Hari ini kamu sudah mengajarkan bapak sesuatu. Kamu dan sajadah merah lusuhmu ini sudah mengajarkan kami semua satu pelajaran paling berharga, Arga. Seisi gedung ini, tidak satupun yang mempunyai sajadah. Padahal orang-orang yang bekerja di perusahaan asuransi ini adalah orang-orang pintar, berpendidikan, dan hidup berkecukupan. Tapi tidak ada satupun yang menyempatkan diri mengingat Allah disela-sela kesibukan mereka mengurusi dunia. Hanya kamu Arga, hanya kamu yang masih sempat bersujud menemui Allah. Bapak yakin Allah ingin menyampaikan pesan kepada bapak, untuk membalas apa yang telah kamu ajarkan pada kami semua. Jangan menunduk saja anakku. Angkat wajahmu, karena sebentar lagi kau akan menjadi manusia mandiri, dengan ilmu yang akan kamu dapatkan.” Beliau dengan lembut menyentuh dagu saya agar wajah ini terangkat dan melihat dunia dari sisi yang baru.
***
Semalaman saya tidak bisa tidur. Memandangi sehelai sajadah merah yang tergeletak di pangkuan saya. Saya amat-amati corak warnanya yang mulai memudar. Di beberapa bagian benang-benang halusnya sudah rontok, meninggalkan bagian-bagian kasar yang menusuk dahi saya ketika bersujud. Sajadah itu peninggalan Bapak sebelum meninggal. Pesan Bapak yang terakhir kali hanya satu, jangan pernah meninggalkan sholat. Ah Bapak! Ternyata wasiatmu telah membuka jendela baru untuk saya, Pak. Jendela harapan untuk bisa melangkah kemasa depan yang lebih baik.
Saya mencium sajadah lusuh peninggalan Bapak itu. Bau apek menyengat hidung saya. Memang sajadah itu belum pernah dicuci dengan sabut semenjak tahun lalu. Meskipun ibu seorang tukang cuci, tapi beliau selalu bilang bahwa sabun cuci itu bukan milik kami, itu milik para majikan ibu. Kami tidak punya hak untuk menggunakan sabun cuci itu untuk kepentingan pribadi. Ibu juga selalu berjanji, nanti, nanti kalau sudah ada uang akan membeli sabun cuci yang wangi untuk mencuci sajadah merah yang lusuh ini.
Malam itu saya berlama-lama bersujud di atas sajadah lusuh. Berkali-kali mengucap syukur kepada Illahi Rabbi akan kemudahan yang telah Ia berikan. Saya semakin percaya bahwa ketika kita menyerahkan keputusan apapun kepadaNya, Allah akan membimbing hamba-hambanya kejalan yang lebih baik. Asal kita tidak berhenti berusaha. Asal kita tidak berhenti berdo’a. Malam itu, air mata saya setetes demi setetes membasahi sajadah lusuh milik Bapak.
***
Bulan Juni 1983
Hari ini saya lulus sebagai seorang sarjana Ekonomi. Cumlaude! Ibu tak henti-henti menghapus air mata yang kerap membasahi pipinya. Kedua adik saya tersenyum bangga menatap saya. Dan di samping mereka berdirilah Ayah – begitu saya memanggil Pak Risman setelah beliau menjadi Bapak angkat saya – yang tidak dapat menyembunyikan haru dibalik wibawanya. Setelah puas memeluk Ibu dan mengucapkan terimakasih atas semua pengorbanannya, saya menghampiri Ayah. Menyalami tangannya. Minta maaf apabila selama saya menjadi anak angkatnya pernah melakukan kesalahan atau menyakiti hatinya. Lalu saya haturkan terima kasih banyak untuk kebaikan hatinya kepada keluarga kami. Beliau hanya tersenyum, menyentuh bahu saya yang bergetar, dan berbisik,
“Sekarang kamu sudah jadi manusia dewasa. Melangkahlah Nak. Jangan ragu.”
***
Setelah lulus kuliah, saya berniat untuk memulai usaha sendiri. Terinspirasi oleh Ibu, saya mulai membuka usaha cuci pakaian, atau yang sekarang dikenal dengan Laundry atau Dry cleaning. Pada awalnya banyak yang meragukan kemajuan usaha saya. Pada saat itu memang usaha mencuci pakaian belum besar seperti sekarang. Namun saya memberanikan diri. Target saya adalah hotel-hotel besar di Jakarta. Saya memulai usaha itu dengan hanya memiliki satu tenaga kerja, Mugi, ingatkan? Teman saya di perusahaan asuransi dulu.
Selangkah demi selangkah saya menjalani usaha tersebut. Tentu dengan bimbingan dari Ayah dan do’a yang tak terputus dari Ibu. Usaha itu membawa berkah yang tak putus. Sebuah usaha yang tadinya banyak diragukan orang kini berkembang dengan pesat. Dari satu tempat cuci baju berkembang menjadi dua, tiga, empat, dan kini sudah ada sekitar 75 yang tersebar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Saya mulai merambah ke usaha lainnya, terutama dalam bidang media. Usaha majalah, radio, hingga pertelevisian saya jalankan. Kini saya sedang mempersiapkan pembukaan maskapai penerbangan. Modal saya satu. Berusaha untuk tidak meninggalkan sholat. Sebagai pengusaha godaan saya sangat besar, dimanapun saya melangkah, kemana pun wajah saya menghadap. Sholatlah yang selalu membenarkan kembali niat saya ketika mulai bergeser. Sholatlah yang mengingatkan saya bahwa yang saya dapat di dunia semata-mata hanyalah bekal untuk akhirat.
***
Yah orang banyak yang tidak percaya ketika mendengar perjalanan hidup saya. Tapi perjalanan hidup saya adalah kenyataan, bukti bahwa Allah-lah Perencana paling sempurna. Cukuplah kita menjalankan perintahNya, dan Dia yang akan menjaga serta membimbing langkah kita.
Dan kisah hidup saya, dimulai dari sehelai sajadah lusuh.
Label: kisah nyata